Ada ungkapan yang mengatakan, “Jika mata dibalas dengan mata, maka seluruh dunia akan buta.” Kini, tampaknya dunia sedang merasakannya. Meski semakin banyak hal yang bisa dilihat dan dijangkau, tampaknya orang-orang malah semakin “buta”.
Berkat teknologi, kita bisa dengan cepat tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain. Seharusnya ini adalah hal yang positif. Kita jadi bisa tahu banyak hal baru. Kita bisa bertemu dan berinteraksi hal-hal yang tadinya terlalu jauh untuk kita jangkau. Kita membayangkan batas antarnegara menjadi kabur dan kita semua bisa menjadi satu warga dunia yang saling terhubung, saling mendukung.
Namun, ketika mengintip warna media sosial tempat “seluruh warga dunia menjadi satu”, saya melihat realita yang hampir bertolak belakang. Narasi-narasi bernada kebencian antar golonganantargolongan sepintas tampak mendominasi. “Cepat tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain” menjadi pedang bermata dua, terlihat dari betapa cepat kabar Trump selaku presiden Amerika Serikat memberlakukan tarif impor mencekik ke negara-negara yang dianggap “tidak menguntungkan AS” ataupun mengesahkan peraturan-peraturan diskriminatif terhadap imigran dan pelajar asing dengan dalih “melawan antisemitisme”. Penyebaran yang cepat berarti reaksi yang cepat pula. tak terhitung banyaknya komentar yang menghujat AS, kelompok konservatif, Yahudi, zionis, atau label-label lain yang dibalas lagi dengan kebencian yang tak kalah kuat.
Mungkin ada yang berpikir debat kusir di internet tidak cukup nyata, tidak perlu diambil pusing. Namun, kita bisa melihat media massa maupun pemerintah berbagai negara mulai mengambil sikap yang juga melanggengkan pandangan “kami vs mereka”. Tidak perlu melihat jauh-jauh, tendensi presiden kita yang sangat pro-militer dengan alasan “melindungi bangsa dari ancaman asing” adalah salah satunya. Puncaknya adalah Trump melangkahi senat dengan menitahkan militer AS untuk menjatuhkan bom di Iran untuk menanggapi serangan Iran terhadap Israel.
Sebelum Trump berulah pun sebenarnya sentimen “kami vs mereka” ini sudah sangat terasa di jagad maya. Sejak Israel terang-terangan menyerang Palestina, seluruh dunia akhirnya melek dengan isu ini dan getol menyerukan pemboikotan terhadap Israel dan hujatan terhadap kaum Yahudi. Kemarahan terhadap Yahudi ini dianggap sah karena mereka telah melakukan kejahatan terhadap suatu kaum. Sebaliknya, kaum Yahudi juga memiliki trauma menjadi korban kejahatan kemanusiaan di tangan Nazi Jerman pada era perang dunia lalu. Tak jarang trauma ini diungkit kembali di tengah-tengah aksi kemarahan terhadap (seharusnya) penjahat perang dan jadi menyakiti mereka yang tidak terlibat. Kaum Yahudi seluruh dunia dan orang-orang yang bersimpati pada penderitaan mereka pun terpancing untuk ikut-ikutan marah. Mereka juga merasa kemarahan mereka “sah” karena melihat diri mereka sebagai korban.
Baca juga: Menyumpahi Orang Celaka, Karma Burukkah?
Sasaran kemarahan mereka yang bersimpati pada kaum Yahudi adalah umat Muslim. Palestina sendiri identik dengan komunitas Muslim dan umat Muslim sedunia merasakan solidaritas yang sangat kuat dengan mereka. Di jagad maya Indonesia sendiri, seruan untuk mendukung Palestina dan menentang zionis terdengar sangat lantang, bahkan terkadang melebihi dukungan untuk bencana kemanusiaan yang terjadi di dalam negeri atau negara-negara lain yang lebih dekat secara geografis. Komunitas Muslim dunia sendiri masih belum pulih dari stereotip negatif akibat aksi terorisme berkedok agama dan friksi imigran dari Timur Tengah yang mencari suaka ke negara-negara Eropa. Ini pun menjadi justifikasi serangan terhadap umat Muslim dan balasan yang tak kalah tajam.
Konflik antara pendukung Israel dan Palestina hanyalah salah satu contoh dari berbagai isu sosial yang membuat dunia seolah terbelah walau bisa jadi pemicunya merupakan yang terparah. Ada juga persoalan tentang gender dan orientasi seksual, ras, bentuk tubuh, dan masih banyak lagi. Meski topiknya berbeda, polanya sama. Masing-masing pihak yang berseteru merasa kemarahannya sah karena mereka terlebih dulu disakiti.
Adakah yang bertanya mengapa ini bisa terjadi? Atau semua menganggap kekacauan ini sudah sewajarnya, bahwa manusia memang akan selalu berkonflik?
Selama enam tahun Siddhartha Gautama duduk merenungkan obat untuk kelahiran, usia tua, sakit, dan mati, tak pernah ada catatan eksplisit mengenai pertanyaan apa saja yang Beliau renungkan. Namun, bukan tak mungkin pertanyaan di atas sempat muncul barang sepintas karena sekarang kita bisa menemukan jawabannya dalam khasanah ajaran sang Buddha.
Karma di Balik konflik
Siapapun yang cukup akrab dengan Buddhisme pasti pernah mendengar ungkapan “aku mewarisi karmaku sendiri”. Ini umumnya diartikan sebagai pemikiran bahwa apapun yang dialami seseorang merupakan akibat dari karma yang diperbuatnya di masa lampau. Pertanyaannya, bagaimana dengan penderitaan yang dialami oleh suatu suku, kelompok, atau bangsa? Apakah ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang “kebetulan” melakukan karma yang sama?
Dari sini kita bisa melihat betapa kompleksnya karma. Tentu saja sekian juta orang Palestina tidak “kebetulan” melakukan karma buruk yang sama sehingga sama-sama ditindas tentara Israel. Karma seperti ini disebut “karma kolektif”, suatu karma yang matangnya dialami oleh banyak orang secara bersamaan karena mereka dulu bersama-sama terlibat dalam karma penyebabnya. Pengalaman setiap individu mungkin berbeda karena tindakan persis yang dilakukan masing-masing orang di masa lampau juga beragam, jadi meski sama-sama dilanda perang, ada yang meninggal, ada yang bertahan hidup, dan ada yang “aman” di negara lain. Namun, mereka tetap memiliki kesamaan sebagai satu bangsa.
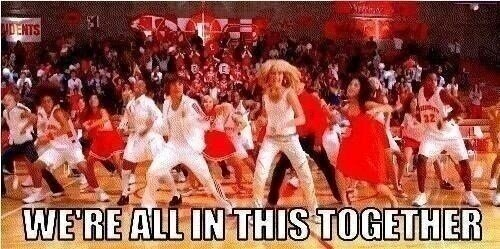
Setelah memahami soal adanya karma kolektif ini, apakah “ditindas kelompok lain” masih bisa menjadi alasan yang sah untuk balas menyakiti kelompok penindas tersebut? Penindasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, tapi jika siapapun yang bertindak sebagai hakim atau algojo untuk “menghukum” pelakunya, hanya akan menghimpun karma buruk bagi dirinya sendiri. Jika “penghukuman” ini dilakukan secara berkelompok, maka karma kolektif baru pun terbentuk. Dengan begitu, konflik tidak akan pernah berakhir.
Lebih lanjut, ketika kelompok lain ikut melakukan “penghukuman” atas nama solidaritas, entah itu dengan serangan militer, kekerasan terhadap perseorangan, atau hujatan di media sosial, maka satu kelompok baru terlibat dalam lingkaran setan karma buruk kolektif ini. “Jika mata dibalas dengan mata, seluruh dunia akan buta” pun menjadi benar adanya.
Ketidaktahuan yang Mengakar
Ketika pemberitaan tentang konflik menjadi makanan sehari-hari, kita terkadang melupakan bahwa semua pihak yang terlibat pada dasarnya sama: takut akan penderitaan dan ingin bisa bahagia. Namun, kebodohan batin yang mengakar sejak berkehidupan-kehidupan lampau membuat orang salah fokus sehingga memunculkan konsep ada “aku” dan “yang lain”. Dari situ, muncullah sikap membeda-bedakan: teman harus disayang, musuh harus dilawan.
Ketika setiap hari muncul berita yang menyoroti konflik, orang-orang melihat “kelompok itu menyakiti kelompokku”, padahal kenyataannya adalah “kelompok itu sedang mencari kebahagiaan sama sepertiku, tapi cara yang mereka tahu ternyata menyusahkan orang lain”. Kesalahpahaman ini bukan hanya menjadi biang kerok perang antar negara atau golongan, tapi juga mendasari berbagai permasalahan kita sehari-hari. Misalnya ketika dikritik, hal pertama yang muncul di pikiran kita adalah “si anu sedang menyerang saya”, padahal si anu hanya ingin mengemukakan pendapat. Kenyataannya, kita sendiri pun pernah mengkritik hanya untuk menyampaikan isi pikiran tanpa keinginan untuk sengaja menyerang orang tertentu bukan?

Hal ini jadi semakin konyol ketika terjadi pada kita saat menyaksikan pemberitaan konflik internasional. Apa yang dilakukan oleh orang lain di belahan dunia lain entah bagaimana caranya bisa membuat kita begitu terluka sehingga kita tidak tahan untuk bereaksi dengan amarah. Di satu sisi, bisa berempati dengan orang-orang yang jauh adalah hal positif, begitu pula dengan kesadaran tentang apa yang adil dan tidak adil. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kemarahan yang bersifat reaktif akan menjadi sebab karma buruk baru yang memperparah keadaan.
Baca tentang definisi, bahaya, dan penawar untuk kemarahan di sini dan di sini.
Ketika respon kita mentok pada mengekspresikan kemarahan, melontarkan hujatan yang kita anggap “sanksi sosial” ke awanama di media sosial, dan mendukung persekusi terhadap pihak yang kita anggap “pantas menderita” tanpa proses perenungan apapun, hampir pasti pengaruh kemarahan dan kebencian pada saat itu lebih kuat dibanding welas asih. Satu orang melakukan hal tersebut akan mendatangkan karma buruk bagi diri sendiri. Bayangkan apa yang terjadi ketika 100 orang melakukan hal yang sama? Lebih lanjut, bayangkan apa yang terjadi ketika kemarahan reaktif seperti itu dianggap benar? Berapa banyak orang yang ikut melakukan, didorong untuk melakukan, atau bahkan merasa terkucilkan ketika tidak melakukan hal tersebut? Sebesar apa dampak karmanya?
Lawan dari Ketidaktahuan
Ketidaktahuan dalam Buddhisme disebut “avidya”. Secara harfiah, kata ini dibentuk dari bahasa Sanskerta “vidya” yang diberi awalan negasi “a-”. Kata “vidya” sendiri berarti kebijaksanaan. Sama halnya dengan kasus ini. Jika kemarahan reaktif disebabkan oleh ketidaktahuan, maka ketika ketidaktahuan itu diatasi, kita akan memiliki kebijaksanaan untuk melihat realita sebagaimana adanya dan menentukan sikap yang terbaik bagi semua pihak.
Lantas, seperti apa realita itu? Jika mereka yang diliputi ketidaktahuan melihat dunia terdiri atas kubu-kubu yang berselisih, maka realita yang sesungguhnya adalah sebaliknya, bahwa semua orang pada dasarnya sama: sama-sama takut menderita dan mendambakan kebahagiaan. Namun, masing-masing orang hanya bisa memperjuangkan kebahagiaan mereka dengan cara yang mereka tahu dalam batasan karma, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Begitu kita membayangkan diri kita berdiri di posisi orang lain, kita akan menemukan bahwa tidak ada siapapun yang bisa kita salahkan.
Selain itu, hubungan kita dengan orang lain juga tidak kekal. Orang yang memusuhi kita di kehidupan ini bisa jadi merupakan sahabat dekat kita di masa lampau. Bahkan dalam lingkup kehidupan ini pun kita pasti pernah mengalami atau setidaknya menyaksikan fenomena serupa. Buat apa kita menghabiskan tenaga untuk bersitegang sekarang?
Buddha bahkan mengungkap kebenaran yang lebih radikal: bahwa semua makhluk, termasuk penjahat perang dan orang-orang yang adu hujat dengan kita di media sosial, sesungguhnya pernah menjadi ibu kita. Ini mungkin terjadi karena setiap makhluk telah mengalami tak terhingga kelahiran dalam siklus lahir-mati di samsara ini.
Kalau mata tidak dibalas dengan mata, dibalas dengan apa?
Setelah mengetahui semua realita ini, jelas bahwa membalas kebencian dengan kebencian bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga sia-sia dan tidak masuk akal. Sebagai gantinya, Buddha menganjurkan kita untuk memadamkan api kemarahan dengan cinta kasih.
Cinta kasih ini tentu tidak bisa dipaksakan muncul tiba-tiba, apalagi dalam konteks perselisihan di jagad maya tempat orang-orang bisa berseteru tanpa saling mengenal. Namun, setidaknya kita bisa mengendalikan diri agar tidak lanjut menyakiti. Ini penting untuk menghentikan siklus pelaku-korban yang telah dijabarkan sebelumnya.
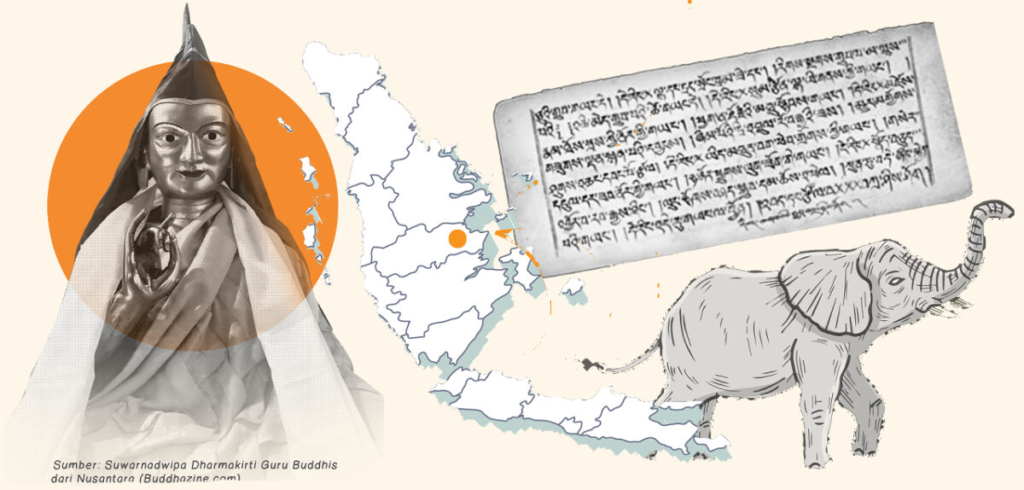
Dalam skala pribadi, kita perlu benar-benar memahami cara karma dan batin bekerja. Minimal kita bisa mengenali emosi atau faktor mental apa yang muncul saat kita hendak “membela” sesuatu dan karma macam apa yang kira-kira akan kita himpun. Jadi, kita punya kesadaran penuh atas tindakan yang kita pilih alih-alih sekadar terbawa arus. Jika kita terpancing ingin marah-marah pada penindas, misalnya, kita bisa mengalihkan perhatian kita dan tenaga kita pada kebutuhan korban, membagikan cara-cara menyalurkan bantuan, memberikan semangat untuk aksi-aksi kemanusiaan, atau bahkan menghimpun kebajikan untuk dilimpahkan pada berakhirnya penderitaan dan terwujudnya perdamaian.
Dalam skala yang lebih besar, kita bisa mempelajari gerakan-gerakan tanpa kekerasan seperti perjuangan Mahatma Gandhi untuk kemerdekaan India dan Y.M.S. Dalai Lama untuk pelestarian budaya Tibet. Tidak ada gerakan yang sempurna, tapi setidaknya kita perlu membuka wawasan tentang opsi lain dalam memperjuangkan keadilan. Ternyata ada lho cara-cara selain menyerukan perang atau balas dendam!

Jika pemahaman Dharma kita sudah lebih mendalam, kita akan menyadari bahwa penderitaan ataupun rasa tidak nyaman yang kita alami adalah karma buruk yang perlu kita tanggung. Ini termasuk komentar, kiriman media sosial, ataupun berita apapun yang membuat kita kesal atau resah meskipun tidak secara langsung ditujukan kepada kita. Setelah menyadari hal tersebut, kita makin mantap untuk mengambil kendali atas reaksi kita terhadap karma tersebut: apakah kita mau mengikuti dorongan kemarahan atau menenangkan diri untuk mencari solusi yang lebih bijak?
Lebih lanjut lagi, ketika batin kita sudah lebih matang, kita akan bisa melihat segala bentuk perselisihan dari sudut pandang Buddhis: bahwa semua pihak sama-sama sedang menderita dalam siklus kebencian di samsara. Keinginan untuk menolong akan mengalir secara alami dan tercermin dalam setiap tindakan kita. Kita bahkan mungkin bisa punya cukup kemampuan dan kebijaksanaan untuk membuka mata orang-orang di sekitar kita sehingga mereka juga tidak ikut meneruskan siklus kebencian yang terlanjur terjadi. Satu orang ini akan mengajak satu orang lain, dan begitu seterusnya hingga karma kolektif baru tercipta: suatu karma kolektif yang berlandaskan kebijaksanaan dan welas asih sehingga menghasilkan dunia yang damai dan tercerahkan alih-alih buta akibat balas dendam yang tak ada akhirnya.


