Bahrul Amsal, dosen Sosiologi Universitas Makassar, menulis di kolom opini Harian Kompas mengenai “spiritualitas digital”, sebuah fenomena di mana praktik keagamaan seseorang jadi terpatok pada kegiatan maya dan dinilai dari “keaktifan” yang terpampang di media sosial. Apakah ini juga terjadi di kalangan Buddhis? Kemungkinan besar jawabannya adalah “ya”. Sejak pandemi, puja bakti maupun ceramah Dharma umum dilakukan secara daring. Pos di media sosial mengenai penggalangan dana dan bakti sosial yang baru digelar adalah hal wajib. Semakin banyak pula akun-akun Buddhis yang membagikan kutipan kitab suci tanpa interpretasi atau penjelasan kontekstual. Demikianlah “kehidupan” umat Buddha di ruang maya.
Ilusi Kebenaran
Internet memang merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Bahkan pecinta buku sekalipun kesulitan menahan godaan kemudahan pencarian Google, apalagi mayoritas orang Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi terendah. Ketika kita mencari definisi “Buddha” di Google misalnya, yang kita dapat adalah biografi manusia bernama Siddhartha Gautama yang hidup di abad VI M.
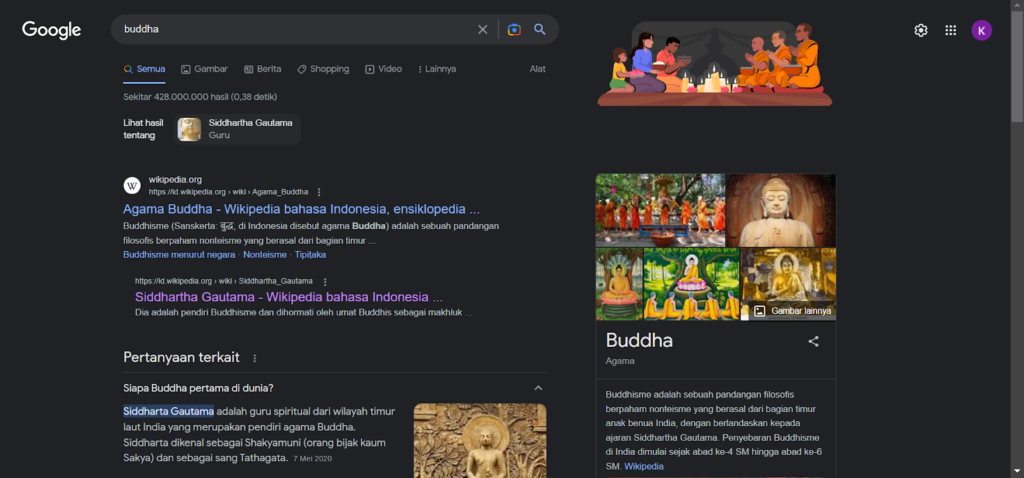
Butuh usaha lebih jauh untuk menemukan bahwa Buddha sesungguhnya adalah sebutan untuk pencapaian kesempurnaan tertinggi dengan kebijaksanaan dan welas asih yang sempurna serta kemampuan yang tak terbayangkan. Namun, berapa banyak orang yang berupaya mencari lebih jauh? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka sudah “cukup jauh” dan mendapatkan jawaban yang tepat? Satu hal yang pasti, tak sedikit yang hanya berhenti di hasil pencarian pertama dan menganggapnya sebagai kebenaran.
Selain mesin pencari, sumber informasi lain yang paling diandalkan adalah media sosial. Sekarang, kita bisa dengan mudah menemukan konten tentang kejadian sehari-hari yang ditempeli kutipan Dhammapada atau bagian lain dari kitab suci. Kutipan ini tidak selalu disertai dengan penjelasan dan bahkan tidak selalu sesuai konteks. Berapa banyak orang yang menekan tombol like dan share sebelum benar-benar merenungkan isi konten tersebut?
Ilusi Praktik Dharma
Lebih lanjut, melalui media sosial, seseorang bisa dengan mudah mencerap “kebenaran” yang diakui oleh rekan-rekannya. Ketika 3 orang berturut-turut menunjukkan aktivitas berdana di Instagram misalnya, orang yang mengikuti ketiga orang itu akan punya pemikiran bahwa “kalau berdana, harus update di Instagram” sebagai hal yang lazim dilakukan.
Pemahaman berikutnya akan sangat bergantung pada kondisi batin orang tersebut. Bisa jadi ia merasa itu adalah sebuah keharusan dan segera mengikuti, atau ia merasa tidak suka dan menganggap itu adalah aktivitas pamer yang tidak perlu. Idealnya tentu orang itu cukup bermudita cita, ikut berdana dengan motivasi yang bajik, lalu move on dengan kehidupannya sendiri tanpa merasa tertuntut untuk ikut update di Instagram.
Tak dapat dipungkiri bahwa mengabarkan aktivitas apapun di media sosial sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang, termasuk kegiatan pengumpulan kebajikan. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kita bisa jadi bermudita dan ikut “tertular” semangat melakukan kebajikan ketika melihat banyak orang lain melakukan hal yang sama. Di sisi lain, jika kita tidak punya ingatan dan kewaspadaan terhadap apa yang terjadi di batin kita, kita akan rawan terjerumus dalam iri hati atau kesombongan. Kemungkinan paling ekstremnya adalah fenomena spiritualisme digital yang dibahas di atas, yaitu timbulnya pemikiran bahwa media sosial menjadi penentu apakah seseorang adalah Buddhis atau bukan.
Spiritualis Digital Mencari Akar
Salah satu tanda seseorang benar-benar menjadi “Buddhis” adalah ketika ia sudah Tisarana (berlindung kepada Triratna: Buddha, Dharma, dan Sangha) dalam pikiran dan perbuatan. Lamrim telah merinci bahwa untuk sampai ke tahap itu, seseorang harus memiliki sebab berlindung yang tepat dan mampu mengidentifikasi objek perlindungan secara tepat. Setelah itu, ada tolok ukur yang bisa dijadikan patokan serta sila-sila yang perlu dijaga agar praktik Tisarana tidak merosot.
Ketika sumber informasi utama kita adalah baris pertama di mesin pencari atau konten dengan like terbanyak dan paling sering muncul di media sosial, hampir tidak mungkin bagi kita untuk Tisarana dengan sebab yang tepat serta mengenali ketiga Ratna dengan pasti. Jika kita melihat aktivitas wihara di media sosial misalnya, yang kita lihat adalah foto puja bakti atau poster ceramah Dharma dengan tema seputar self-help yang 11-12 dengan seminar motivasi. Sejauh mana hal-hal ini bisa mencerminkan ketakutan terhadap alam rendah dan pemikiran tentang kehidupan mendatang? Apakah ceramah “Menjadi Sukses ala Buddhis” memberikan informasi bahwa Dharma dalam definisi tertinggi adalah kebenaran Arya tentang terhentinya dukkha dan jalan penghentian dukkha?
Jika kita cukup beruntung untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung, mungkin kita bisa menemukan esensinya. Namun, untuk sekian banyak “spiritualis digital” yang membentuk identitas agamanya dari apa yang bisa dilihat di internet, harus ada sumber Dharma autentik yang diantarkan langsung kepada mereka.
Bukan Hanya Warganet yang Butuh
Perlu diingat bahwa “spiritualis digital” ini bukan sindiran terhadap generasi yang malas menggali informasi, tapi juga mencakup orang-orang yang tulus ingin menempuh kehidupan spiritual, tapi terhalang oleh berbagai hal. Bisa jadi ada umat agama lain yang tertarik pada Buddhadharma, tapi malu untuk datang langsung ke wihara. Atau ada juga orang-orang dari kelompok minoritas gender dan seksualitas yang merasa lebih aman di dunia maya. Dan tentunya, banyak orang-orang di daerah terpencil yang tak punya akses langsung terhadap materi ataupun pengajar Dharma sehingga hanya bisa mengandalkan kearifan leluhur yang terus digempur zaman.
Di Indonesia sendiri, persebaran materi, kegiatan, dan komunitas Dharma terfokus pada kota-kota besar. Tak sedikit umat Buddha yang ada di desa-desa terpencil, misalnya di wilayah Jawa, yang bahkan tak memiliki anggota Sangha yang tinggal untuk membimbing secara permanen. Ketika materi tertulis dan sosok panutan tak tersedia, tentunya persepsi terhadap Buddhadharma jadi amat bergantung pada apa yang bisa ditemukan dengan mudah di internet.
Bagi umat Buddha di daerah pelosok, terutama desa-desa di Jawa yang merupakan keturunan leluhur dari peradaban Buddhis Nusantara di masa kejayaannya, teknologi menjadi penolong sekaligus ancaman. Di tempat-tempat yang sudah mendapatkan akses internet, umat Buddha Jawa bisa terhubung dengan dunia luar dan menjangkau tak terhingga banyaknya pintu Dharma yang tersebar di dunia maya. Internet juga bisa menjadi sarana untuk menunjukkan keberadaan mereka di dunia luar beserta segala kesenian dan budaya Buddhis Nusantara yang selama ini tak banyak diketahui masyarakat. Namun, risiko “tertular” virus spiritualitas digital yang datang bersama teknologi tersebut akan selalu ada.

Sumber: Buddhazine.com
Buku Dharma Sebagai Solusi
Tentu ada cara agar umat Buddha di pelosok bisa mendapatkan manfaat dari teknologi tanpa menjadi korban spiritualitas digital. Pertama, kehadiran anggota Sangha atau guru Dharma berkualitas yang secara langsung memberikan bimbingan secara penuh waktu tentu akan sangat membantu. Namun, selain itu, buku referensi tekstual yang membahas topik-topik Dharma secara rinci dan menyeluruh juga perlu disebarkan seluas-luasnya, hingga ke daerah pelosok. Selain tentunya bermanfaat langsung bagi komunitas Buddhis yang belum terpapar teknologi, umat Buddha yang selama ini sudah mulai mengandalkan internet juga bisa melakukan pengecekan lebih lanjut atas informasi yang mereka temukan dengan buku-buku tersebut sebagai acuan.
Buku-buku ini juga perlu memiliki nilai tambah sehingga orang-orang tertarik untuk membaca, misalnya dengan bingkai topik persoalan sehari-hari bagi kawula muda, atau menggunakan bahasa daerah yang lebih akrab bagi penerimanya dibanding bahasa yang digunakan di internet dan media sosial. Format buku digital yang bisa diunduh dengan mudah juga bisa menjadi alternatif lain, walau buku cetak yang bisa dipegang dan dibaca kapan pun tanpa terhalang sinyal tetap harus tersedia. Ini juga akan membantu generasi yang lebih tua di daerah pelosok yang juga haus akan Dharma, tapi lebih sulit mendapatkannya karena keterbatasan literasi teknologi.
oleh Samantha J.
—
Sejak tahun 2017, Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lamrim Nusantara (YPPLN/Lamrimnesia) berkomitmen untuk menerjemahkan buku-buku Dharma ke dalam bahasa Jawa dan membagikannya tanpa pungutan biaya kepada umat Buddha Jawa. Pembagian dilakukan di Waisak Bersama se-Jawa Tengah di Candi Sewu serta dikirim langsung ke desa-desa Buddhis di daerah pelosok.
Dukung kami untuk mengantarkan sumber Dharma berharga kepada umat Buddha Jawa dalam bahasa yang lebih dekat di hati dan berbagai usaha pelestarian Dharma lainnya dengan menjadi Dharma Patron Lamrimnesia.
Donasi dapat disalurkan ke sini atau via transfer langsung ke BCA 0079 388 388 atau MANDIRI 119 009 388 388 0 a.n. Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lamrim Nusantara (tambahkan Rp2,- ke nominal transfer).

